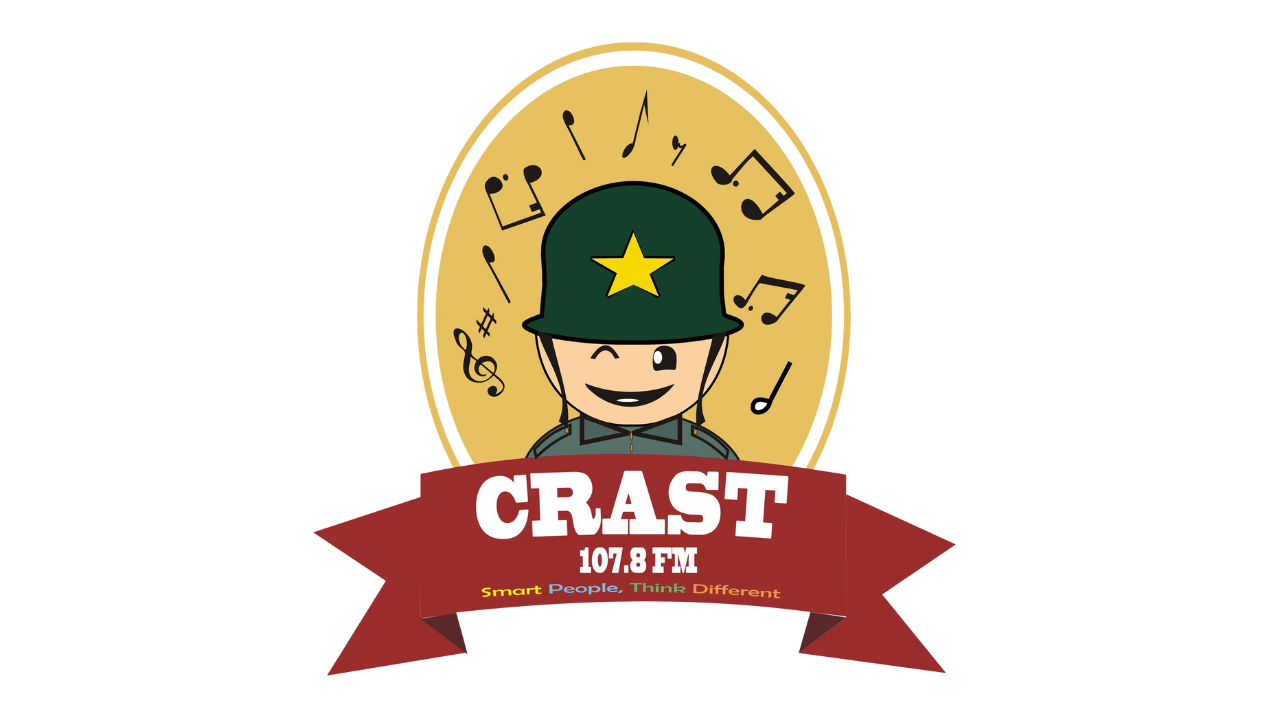Masa kecil saya banyak mendengar lagu-lagu lawas seperti MLTR, Scorpions dan Iwan Fals—mereka semua adalah idola bapak saya. Tetangga saya lain, dia suka sekali memutar campursari dan dangdut. Didi Kempot hingga Om Palapa, Monata dan kawan-kawan masuk telinga saya karena memakai speaker yang radiusnya bisa tiga rumah. Namanya apa sih, sound system? Orang sini biasa menyebut salon.
Maestro campursari itu telah berpulang. Semoga beliau mendapat tempat yang layak di sisi-Nya. Saya cukup menyukai karya-karyanya, bahkan pernah ingin datang konsernya. Alasannya adalah saya suka sekali dengan caranya mencecerkan patah hati di tiap tempat. Tanjung Mas Ninggal Janji, Stasiun Balapan, Terminal Tirtonadi dan masih banyak lainnya. Magisnya dari lagu Didi Kempot, saya bisa merangkai alur di kepala dengan sangat enak untuk cerita yang tepat. Imbasnya, saya patah hati tanpa merasa jatuh cinta.
Sewu Kuto pun luar biasa. Seribu kota hanya untuk mencari sebuah temu. Dan nyeseknya, keridhoan Didi dalam liriknya, “Umpamane koe uwis mulyo, lilo aku lilo..” Sebagaimana mestinya, cinta berbeda dengan kepemilikan. Meskipun sudah melalui liku seribu kota dengan sepanjang jalan kenangan hanya memikirkan semua sisa-sisa yang sia-sia antara saya / kamu dan dia, tetap saja cinta harus dijaga kemurniannya. Kita tidak boleh merasa berhak hanya karena paling lelah berjuang. Jika dia sudah lebih bahagia dan sejahtera, ikhlaskan saja. Didi Kempot melantunkan harapannya, “Aku pengen ketemu..” Ambyar!

Hingga saya dewasa—setidaknya awal usia 20an, saya merasa perpisahan di stasiun itu sangat menakutkan. Jujur saja, ada ruang lagu Didi Kempot di masa kecil yang membentuk pola pikir itu. Menurut saya suara lonceng atau apalah namanya yang menyerukan kedatangan kereta itu mengerikan. Meskipun saya belum merasakan perpisahan di kereta dan tidak bertemu lagi, tapi naluri saya merasa ada banyak orang yang harus menumbuhkan kerelaan itu. Singkatnya, saya menjadi sentimental dengan stasiun. Perihal stasiun adalah saya segera menemuimu atau saya menunggumu kembali.
Didi Kempot selalu menghadirkan cerita tentang prinsip kehidupan ini. Bahwasanya semua hanya soal meninggalkan atau ditinggalkan. Seperti seseorang yang melihat pujaan hati untuk terkahir kali melalui jendela bus antar kota. Seseorang yang melambai di pelabuhan tanpa tahu kapan momentum untuk melepas rindu itu datang lagi.
Belakangan ini saya baru tahu alasan Lord Didi tidak membuat lagu perpisahan di bandara. Katanya, orang yang berpisah di bandara kemungkinan bisa bertemu lagi. Karena kebanyakan dari mereka adalah orang kaya. Tapi jika perpisahan itu di stasiun, pelabuhan apalagi terminal belum pasti bisa bertemu lagi. Sebab kepergian mereka untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dalam perjalanannya, tidak selalu mulus. Ada banyak cerita perantau kehabisan sangu, tak dapat pekerjaan dan bekerja serabutan tak bisa pulang.

Dulu, saya suka heran kenapa kebanyakan lagu Didi Kempot hanya menyoroti putus cinta karena kesenjangan ekonomi. Kebanyakan adalah kita (miskin), tidak layak untuk merasakan nikmatnya cinta hingga pelaminan karena terganjal restu. Menurut saya itu klasik dan mainstream sekali. Tapi saya baru menyadari, kisah klasik selalu menarik. Rasanya ada jutaan orang merasa tidak pantas karena terhalang status kekayaan. Dan Agus Mulyadi melontarkan jika Didi Kempot selalu bersama orang-orang dengan kesedihan berlapis: sudah miskin, tuna asmara pula.
Tapi Lord Didi pun tidak melarang cinta bersemi. Dan kami, boleh merasakan cinta. Tentu saja hingga hari perpisahan itu tiba. Selamat jalan Lord Didi! Meskipun hari perpisaha tiba, kami tetap dan selalu mencintaimu. (Sosa)